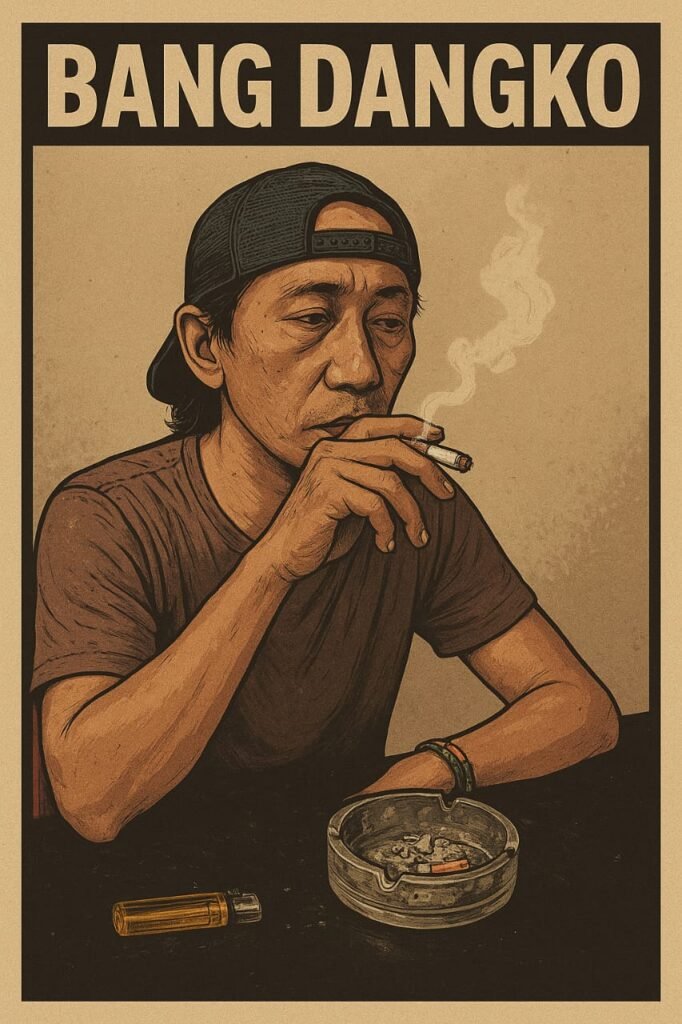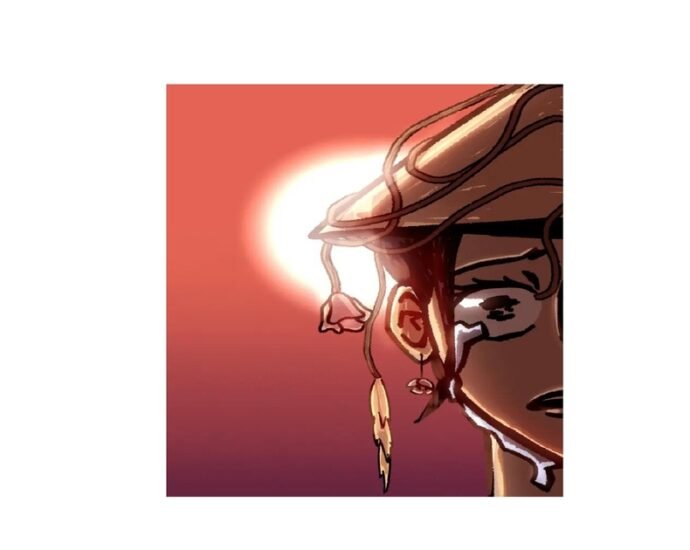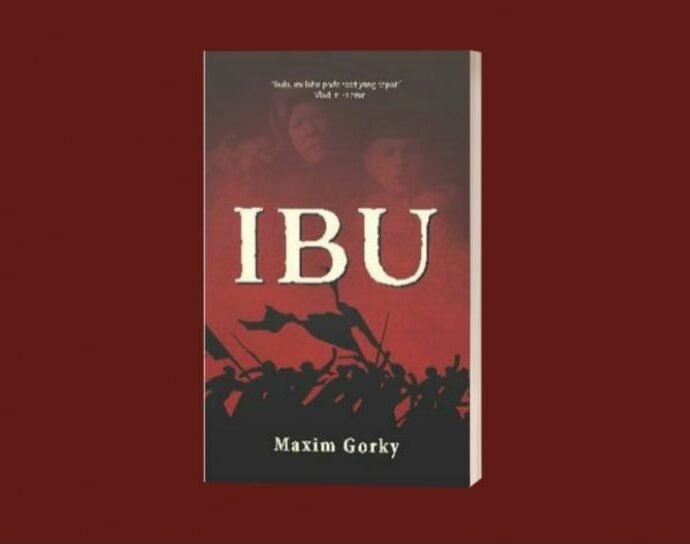Sebuah Paket dari Masa Lalu

Suatu hari di tahun 2025, Annie yang tengah duduk di beranda depan rumahnya tiba-tiba didatangi seorang pengantar paket. Diterimanya paket itu dengan bingung. Tak ada alamat dan nomor telepon di bagian pengirim, hanya tertulis: “Dari masa lalu.”
Dibukanya paket itu dengan rasa penasaran yang berdebar. Ternyata isinya sebuah buku catatan. Beginilah isinya:
Aku tak tahu apa perasaanku kini. Aku tak menangis ketika bus itu bergerak meninggalkan terminal kecil dan menjauhi dirinya yang melambaikan tangan padaku.
“Telepon aku ya, Yang…,” katanya tanpa suara dari balik kaca bus. Tetesan air mata menggantung di pelupuk matanya, membasahi kacamatanya. Kami berawal dari sekuntum mawar layu di kala hujan. Gerimis malam, dingin yang gelap. Kuberikan sekuntum mawar merah padanya tanpa kata.
Kini aku harus berada di atas bus ini, pergi ke Jogja, meninggalkan Jakarta—dan dirinya di dalamnya. Semua karena hidup butuh pekerjaan, untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan manusiawi yang kami punyai.
Aku ingin mengirim pesan singkat padanya, menanyakan apakah ia sudah berhasil sampai di rumah, melewati daerah Senen yang rawan kejahatan. Tapi aku tak punya pulsa. Dan kalaupun aku bisa mengirim pesan singkat itu padanya, ia juga takkan bisa membalas, karena ia pun tak punya pulsa.
Aku hanya bisa memandangi mobil-mobil yang bergerak di jalan tol dan jembatan layang yang megah berkelok. Baru setelah senja, persawahan hijau mulai kelihatan, tanda bahwa Jakarta telah kutinggalkan.
Setelah lama dalam kebisuan yang hanya diisi oleh deru kendaraan, malam ini bus berhenti di rumah makan. Kucoba menghubunginya, tetapi wartel sialan itu tidak bisa menyambungkannya. Malah uang seribu rupiahku dimakannya.
Antre dengan bon makan, aku enggan. Kupergi ke kamar mandi, termenung, menghabiskan sebatang rokok. Aku keluar setelah rokok habis dan setelah gedoran di pintu terdengar bertalu-talu.
Aku ingin menghubunginya lagi, tapi uangku tinggal sedikit. Jika kehabisan uang, tak ada mesin ATM di sekitar sini. Tapi… aku ingin sekali menelepon dirinya. Entah kenapa, aku sangat ingin mengetahui keadaannya. Sebelum kupergi, aku bilang padanya,
“Yang, nanti di Jogja kukirim lagi ya lamaranmu.”
“Yang” berarti sayang—begitu aku selalu memanggilnya, dalam kondisi apa pun. Ia membalas dengan anggukan lemah. “Oke deh, Yang.”
Kami adalah sarjana, tapi masih menganggur, karena susah sekali mencari pekerjaan yang layak di sini. Dia pernah bekerja, tapi cuma dua bulan, karena perusahaan tempat dia bekerja memasang target: jika tak bisa mendapatkan klien dalam waktu dua bulan, maka ia harus menandatangani kontrak untuk tak digaji lagi.
Kami ingin menikah dan hidup mandiri, tapi sepertinya sekarang itu semua susah sekali. Orang tua hanya akan mempermudah pernikahan jika sudah lulus dan dapat pekerjaan yang layak. Seperti yang dikatakan ibuku suatu malam padanya,
“Annie, Tante setuju kalian menikah. Itu semua terserah kalian. Tapi Haris kan baru lulus dan belum dapat pekerjaan. Bagaimana nanti jika kalian hidup kesusahan?” Alasan mereka sebenarnya masuk akal, agar kami bisa hidup tanpa kekurangan apa pun. Tapi apakah sebuah pernikahan—penyatuan dua hati—harus ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita hasilkan?
Sebenarnya sudah ratusan lamaran kerja kukirimkan ke ratusan perusahaan, atas nama dirinya dan atas namaku. Tapi entah kenapa pekerjaan yang diinginkan susah sekali didapat. Kalaupun dapat, kadang ia tak mau, karena perusahaan selalu mematok target: dalam berapa bulan ia harus mendapatkan klien atau pelanggan agar bisa bertahan di perusahaan. Ini yang membuat dirinya kemudian tak menyukai pekerjaan di bidang pemasaran.
“Kenapa memangnya kalau marketing, Yang?” tanyaku di atas bus kota.
“Susah, Yang, kalau marketing. Aku dituntut untuk memenuhi target dan harus bekerja di bawah tekanan.”
“Tapi, Yang, coba dululah. Tentu saja kita ditekan. Kufikir tekanan adalah hal yang wajar. Perusahaan tentu tak ingin rugi. Lagian kita kan bukan pemilik perusahaan,” jelasku, yang kemudian diikuti anggukan lemah olehnya.
“Oke deh, Yang, kucoba.”
Pekerjaan bagi kami adalah jalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi: berumah tangga dan hidup mandiri. Kami ingin membuktikan pada mereka bahwa kami bisa hidup mandiri, dan karena itu kami pantas menikah.
Aku jadi teringat pada hari-hari yang indah, yang kulewati bersamanya—pelukannya, ciumannya.
“Aku cinta kamu, Yang.” “Aku cinta kamu juga, Yang.”
Kami tak rela semua ini harus terhalang oleh persyaratan agar kami bisa menikah. Padahal sebenarnya, kami akan tetap berusaha bertahan seburuk apa pun kondisi keuangan setelah menikah. Karena bagi kami, susah ataupun senang harus dihadapi bersama. Begitulah perjanjian kami selama ini, yang sudah kami anggap sebagai pakta, sebagai akad kami berdua.
Menurut bapakku, ketika ia dan ibuku menikah, ia juga belum bekerja. Ibukulah yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menikah setelah bapakku lulus dari fakultas kedokteran. Awalnya mereka pun tak mendapat restu dari orang tua masing-masing, tapi mereka tetap menikah akhirnya. Tapi kenapa mereka tak belajar dari masa lalu itu? Kenapa mereka harus memberikan syarat-syarat seperti ini?
Mereka pernah bilang padaku, “Nak, bukannya kami tak merestui pernikahanmu. Tapi lihatlah, Nak, sekarang dan dulu berbeda. Dulu ketika aku menikah dengan bapakmu, uang seratus rupiah itu masih terasa besar sekali. Sekarang seratus ribu saja terasa kecil. Harga hidup sekarang mahal, Nak.”
Mendengar itu, aku hanya bisa pergi ke balkon belakang, memandangi malam, menatap jutaan bintang. Bus masih terus melaju kencang di tengah kegelapan malam. Terkadang berkelok menikung tajam. Beberapa kali aku ke toilet di bus ini untuk buang air kecil; AC-nya terlalu dingin hingga rasanya aku ingin buang air kecil sesering mungkin.
Perjalanan pulang ke Jogja berbeda sekali rasanya dengan perjalanan ke Jakarta bersama dirinya beberapa hari yang lalu. Saat itu ia tertidur dengan nyaman, menyandarkan kepalanya di bahuku, dengan kedua lengannya memeluk lengan kananku. Walaupun kami hanya naik kereta ekonomi tanpa AC, bagi kami rasanya seperti naik pesawat kelas utama.
Bus masih melaju kencang, sesekali miring karena memotong melewati kendaraan lain. Aku agak cemas, karena kulihat si sopir dari tadi menenggak minuman dari botol itu—minuman keras yang bisa membuatnya mabuk berat dan kehilangan kesadaran.
Mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan seperti yang sering kulihat di berita. Aku masih ingin hidup untuk mewujudkan impian-impian kami—impianku dan Annie yang belum terwujud. Aku ingin menikah, mempunyai anak yang akan kami besarkan bersama dengan cinta.
Kuraih selimut di sandaran bangku bus. AC bus ini semakin dingin, bercampur dinginnya malam yang menggigit, menulang. Musik mengalun, dan sebuah lagu mengingatkanku pada Annie dan perjuangan kami berdua:
Tommy used to work on the docks
Union’s been on strike, he’s down on his luck
It’s tough, so tough
Gina works the diner all day
Working for her man
She brings home her pay for love
Mm, for love
She says, “We’ve gotta hold on to what we’ve got
It doesn’t make a difference if we make it or not
We got each other, and that’s a lot for love
We’ll give it a shot”
Oh, we’re half way there
Oh-oh, livin’ on a prayer
Take my hand, we’ll make it, I swear
Oh-oh, livin’ on a prayer
Aku terlelap ketika lagu itu belum sempat berakhir. Menghadirkan mimpi indah tentang kami yang berpelukan berdua dengan cinta, di tengah hamparan bunga warna-warni.
“Aku cinta kamu, Annie sayang…”
“Aku cinta kamu juga, Haris sayang…”
Aku terbangun dengan tak rela ketika sebuah benda keras menghantam kepalaku—salah satu koper milik penumpang bus jatuh dari tempat penyimpanan barang di langit-langit bus. Kulihat bus telah kehilangan kendali. Sopirnya kehilangan kesadaran. Minuman itu telah membuatnya mabuk. Kecemasanku terwujud, dan bus melesat menghantam apa saja dalam kegelapan malam. Para penumpang yang juga terjaga tiba-tiba berteriak histeris ketakutan.
Dan… apa yang terjadi, terjadilah. Bus menghantam benda yang sangat keras, dalam keadaan terbalik kaki di atas, kepala di bawah. Aku tak bisa melihat apa-apa; semuanya gelap gulita.
“Tolong, siapa saja, sampaikan pada Annie… aku sangat mencintainya. Aku pasti…pasti menikahinya. Kami akan berumah tangga, membesarkan anak kami bersama. Tolong… tolong…”
Annie menutup buku catatan tersebut dengan air mata berlinang. Ia memang menunggu kabar dari kekasihnya, Haris, dulu. Bertahun-tahun tiada berita, hingga akhirnya ia memutuskan menikah dengan Usman. Sekarang mereka sudah punya dua anak. Yang paling tua sudah kelas tiga SMA, sementara yang paling kecil baru berusia empat tahun.
Ia berdoa kemudian, sembari memejamkan mata, supaya di mana pun Haris berada, senantiasa diberi kemudahan dan keselamatan oleh Tuhan. Ditatapnya langit sore, dan ia berbisik lirih,
“Haris, semoga kamu tenang di mana pun kamu berada.”
Karya: Harsa Permata