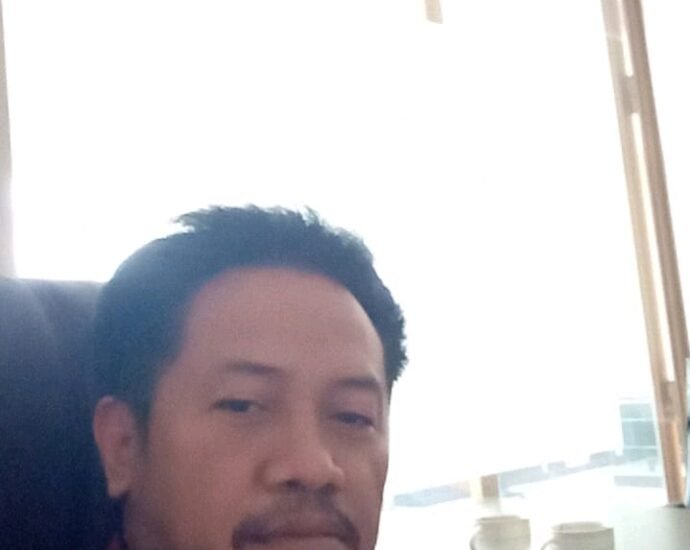Ketika Stabilitas Menggantikan Pikiran

Oleh: RJ. Endradjaja
Politik Indonesia di Zaman Kegilaan Kolektif
Friedrich Nietzsche pernah menulis bahwa kegilaan pada individu adalah sesuatu yang jarang, tetapi dalam kelompok, partai, bangsa, dan zaman, kegilaan justru menjadi aturan. Pernyataan ini bukan metafora psikiatris, melainkan kritik tajam terhadap politik modern: ketika individu berhenti berpikir sebagai subjek, lalu menyerahkan kesadarannya kepada kolektivitas, slogan, dan emosi bersama.
Dalam bahasa aslinya, Nietzsche menulis:
“Im Individuum ist der Wahnsinn etwas Seltenes – aber in Gruppen, Parteien, Nationen und Zeiten ist er die Regel.“
(Dalam diri individu, kegilaan adalah sesuatu yang jarang—tetapi dalam kelompok, partai, bangsa, dan zaman, ia adalah kaidah).
Kegilaan yang dimaksud Nietzsche bukanlah histeria, melainkan penangguhan nalar: kondisi ketika kepatuhan, rasa aman, dan loyalitas menggantikan keberanian untuk berpikir. Politik, dalam situasi seperti ini, tidak lagi membutuhkan argumen—cukup sugesti dan pengulangan.
Fenomena ini hidup subur dalam politik Indonesia kontemporer, terutama di era media sosial, buzzer, dan glorifikasi jargon “stabilitas”.
Massa, Sugesti, dan Kepatuhan Emosional
Gustave Le Bon, dalam “Psychologie des Foules” (1895), memberikan penjelasan psikologis atas intuisi Nietzsche. Menurut Le Bon, individu yang larut dalam massa mengalami regresi mental: kesadaran kritis melemah, digantikan oleh sugesti, emosi, dan naluri kolektif.
Le Bon menulis:
“Dans les foules, c’est l’inconscient qui domine.”
(Dalam kerumunan, yang berkuasa adalah ketaksadaran).
Massa, bagi Le Bon, tidak berpikir—ia bereaksi. Ia tidak menimbang kebenaran, melainkan menelan simbol. Karena itu, massa mudah diarahkan oleh figur otoritatif, slogan berulang, dan narasi sederhana yang memberi rasa aman.
Dalam politik Indonesia, pola ini tampak jelas: perdebatan kebijakan disederhanakan menjadi dikotomi moral, kritik dibingkai sebagai ancaman, dan loyalitas dianggap lebih penting daripada pertanyaan.
Stabilitas sebagai Ideologi
Di titik ini, “stabilitas” berhenti menjadi kondisi objektif dan berubah menjadi ideologi depolitisasi. Stabilitas dijadikan alasan untuk menunda kritik, mengelola ketidakpuasan publik, dan membingkai perbedaan pendapat sebagai gangguan.
Hannah Arendt mengingatkan bahwa bahaya terbesar politik modern bukanlah kekerasan terbuka, melainkan kepatuhan tanpa refleksi. Dalam “Eichmann in Jerusalem“, ia menulis:
“The trouble with Eichmann was precisely that so many were like him, and that the many were neither perverted nor sadistic, but terribly and terrifyingly normal.”
(Masalah dengan Eichmann justru terletak pada kenyataan bahwa begitu banyak orang seperti dirinya, dan bahwa mereka bukan orang-orang yang menyimpang atau sadis, melainkan orang-orang yang sangat normal—secara mengerikan).
Bagi Arendt, kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh fanatik ideologis, melainkan oleh individu biasa yang enggan berpikir (thoughtlessness).
Mereka menjalankan peran dan mematuhi sistem, bukan karena keyakinan ideologis yang mendalam, melainkan karena kegagalan untuk melakukan refleksi dan pertimbangan moral.
Media Sosial dan Administrasi Kesadaran
Dalam konteks hari ini, kekuasaan tidak lagi bekerja terutama melalui represi, melainkan melalui manajemen perhatian. Media sosial tidak memaksa warga untuk percaya; ia cukup mengatur apa yang terus-menerus muncul di layar.
Buzzer politik, influencer partisan, dan mesin framing digital berfungsi sebagai operator sugesti modern. Mereka tidak berargumen, tetapi mengulang. Tidak membantah, tetapi mengaburkan. Dalam logika ini, yang penting bukan benar atau salah, melainkan viral atau tenggelam.
Mengikuti Michel Foucault, kondisi ini dapat dibaca sebagai relasi kuasa–pengetahuan: wacana tertentu diproduksi, direplikasi, dan dinormalisasi, sementara wacana lain disingkirkan tanpa perlu sensor formal.
Ruang Publik yang Kehilangan Nalar
Jürgen Habermas membayangkan ruang publik sebagai arena deliberasi rasional. Namun dalam realitas politik Indonesia hari ini, ruang publik semakin menyerupai pasar atensi. Argumen kalah oleh emosi, dan refleksi kalah oleh kecepatan.
Kelas menengah digital—yang secara historis diharapkan menjadi penjaga nalar publik—sering kali terjebak dalam aktivisme simbolik: lantang secara moral, tetapi jinak secara struktural. Mereka ikut gaduh, namun jarang menyentuh pusat kekuasaan.
Penutup: Melawan Kegilaan dengan Berpikir
Masalah utama politik Indonesia hari ini bukan kekurangan informasi, melainkan keengganan berpikir di tengah kegaduhan media. Stabilitas dijadikan mantra, sementara ketidakadilan dikelola sebagai kebisingan yang harus diredam.
Nietzsche telah memperingatkan bahaya zaman.
Le Bon menjelaskan psikologi massa.
Arendt menunjukkan akibat politiknya.
Kini pertanyaannya sederhana namun mendesak:
“apakah kita masih berpikir sebagai warga, atau hanya bereaksi sebagai massa?”
Dalam politik yang sehat, stabilitas lahir dari keadilan dan nalar.
Ketika stabilitas justru menggantikan pikiran, kegilaan kolektif berhenti menjadi penyimpangan—dan berubah menjadi norma.
*RJ. Endradjaja – Pembelajar Pinggiran